A. Pengertian Pertumbuhan dan
Perkembangan
Semua
organisme dalam hidupnya mengalami proses perubahan biologis. Perubahan
tersebut terjadi disebabkan semua organisme mengalami pertumbuhan dan
perkembangan. Berlang- sungnya proses perubahan biologis dipengaruhi oleh
tersedianya faktor-faktor pendukung. Perubahan tanaman kecil menjadi tanaman
dewasa dan menghasilkan buah berawal dari satu sel zigot menjadi embrio,
kemudian menjadi satu individu yang mempunyai akar, batang, dan daun. Demikian
pula hewan, tumbuh dari satu sel zigot menjadi embrio, kemudian berkembang
menjadi satu individu lengkap dengan organ-organ yang dimiliki, seperti kaki,
kepala, dan tangan. Peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup
yang berupa pertambahan ukuran (volume, massa, dan tinggi) yang bersifat
irreversibel disebut pertumbuhan.
Perubahan
terjadi selama masa pertumbuhan menuju pada satu proses kedewasaan sehingga
terbentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Sebagai
contoh, pertumbuhan tanaman membentuk akar, batang, dan daun. Peristiwa
perubahan yang demikian disebut diferensiasi. Peristiwa diferensiasi
menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi masing-masing
organ, sehingga perubahan yang terjadi pada organisme tersebut makin kompleks.
Proses perubahan bio- logis seperti ini disebut perkembangan. Perkembangan
mengarah pada proses menuju kedewasaan organisme.
Pertumbuhan
dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor dalam dan luar.
Faktor yang terdapat dalam tubuh organisme, antara lain sifat genetik yang ada
di dalam gen dan zat pengatur tumbuh yang merangsang pertumbuhan. Adapun faktor
lingkungan merupakan faktor dari luar yang memengaruhi pertumbuhan. Kemudian,
potensi genetik hanya akan berkem- bang apabila ditunjang oleh lingkungan yang
cocok. Dengan demikian, sifat yang tampak pada tumbuhan dan hewan meru- pakan
hasil interaksi antara faktor genetik dengan faktor ling- kungan secara
bersama-sama.
Pertumbuhan
adalah proses kenaikan massa dan volume yang irreversibel (tidak kembali ke
asal) karena adanya tambahan substansi dan perubahan bentuk yang terjadi selama
proses tersebut. Selama pertumbuhan terjadi pertambahan jumlah dan ukuran sel.
Pertumbuhan dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif.
Perkembangan
adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna. Perkembangan
tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif.
Perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dengan pertumbuhan.
Pertumbuhan
pada tumbuhan terutama terjadi pada jaringan meristem (ujung akar, ujung
batang, dan ujung kuncup). Tumbuhan monokotil tumbuh dengan cara penebalan
karena tidak mempunyai kambium, sedangkan tumbuhan dikotil pertumbuhan terjadi
karena adanya aktivitas kambium. Kambium memegang peranan penting untuk
pertumbuhan diameter batang. Kambium
tumbuh ke dalam membentuk xilem (kayu), ke arah luar membentuk floem. Dalam
pertumbuhan dan perkembangan terjadi pembelahan sel, pemanjangan sel dan
diferensiasi sel.
B. Tahap-Tahap Pertumbuhan dan
Perkembangan Tumbuhan
Pada
proses pertumbuhan dan perkembangannya, tumbuhan mengalami periode lamban yaitu
dengan ciri adanya sedikit pertum- buhan atau tidak ada pertumbuhan yang
sebenarnya. Periode ini terjadi pada saat tumbuhan sedang mempersiapkan diri
untuk tumbuh, misalnya sebutir biji yang sedang menyerap air untuk persiapan
perkecambahan.
Periode
lamban ini akan diikuti dengan periode eksponen (logaritma). Pada periode ini
dimulailah suatu pertumbuhan yang pada awalnya lambat tetapi kemudian semakin
cepat. Fase ini tidak akan terjadi terus menerus. Dalam beberapa waktu
pertumbuhannya akan menurun dan segera mema- suki periode perlambatan.
Pertumbuhannya akan berlangsung lebih lambat dan akhirnya akan berhenti sama
sekali, misalnya terjadi pada pohon yang tumbuh terus menerus sampai suatu
ketika terkena suatu penyakit dan akhirnya akan mati.
1.
Tahap
Awal Pertumbuhan
Pertumbuhan
pada biji telah dimulai pada saat proses fisika, kimia, dan biologi mulai
berlangsung. Mula-mula terjadi proses fisika saat biji melakukan imbibisi atau
penyerapan air sampai biji ukurannya bertambah dan menjadi lunak. Saat air
masuk ke dalam biji, enzim-enzim mulai aktif sehingga menghasilkan berbagai
reaksi kimia.
Kerja
enzim ini antara lain, mengaktifkan metabolisme di dalam biji dengan
mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada saat
perkecambahan berlangsung yang dipakai untuk berkecambah.
Aktivitas
pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Pada tanaman
kecepatan pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut busur
tumbuh atau auksanometer.
2.
Perkecambahan
Perkecambahan
adalah munculnya plantula (tanaman kecil) dan radikula (calon akar) dari dalam
biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada perkembangan
embrio saat berkecambah, bagian plumula tumbuh dan berkembang menjadi batang,
sedangkan radikula menjadi akar.
Tipe
perkecambahan ada dua macam, tipe itu sebagai berikut.
a. Tipe
perkecambahan di atas tanah (Epigeal)
Tipe
ini terjadi, jika plumula muncul di atas permukaan tanah, sedangkan kotiledon
tetap berada di dalam tanah. Hipokotil memanjang sehingga plumula dan kotiledon
ke permukaan tanah dan kotiledon melakukan fotosintesis selama daun belum
terbentuk. Contoh: perkecambahan kacang hijau.
b. Tipe
perkecambahan di bawah tanah (hipogeal)
Tipe
ini terjadi, jika plumula dan kotiledon muncul di atas permukaan tanah. Epikotil
memanjang sehingga plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas
permukaan tanah, sedangkan kotiledon tertinggal dalam tanah. Contoh:
perkecambahan kacang kapri (Pisum sativum).
Makanan
untuk pertumbuhan embrio diperoleh dari cadangan makanan karena belum
terbentuknya klorofil yang diperlukan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil
makanan diperoleh dari kotiledon, sedangkan pada tumbuhan monokotil diperoleh
dari endosperm.
Di
daerah yang memiliki empat musim dalam setahun, pohon tumbuh selama musim semi
dan musim panas. Pertumbuhan terutama terjadi pada ujung pohon, pucuk ranting,
dan akar. Ranting memanjang dan bunga serta daun muncul dari pucuk. Ujung akar
tumbuh memanjang dan menembus lapisan tanah. Akar dan ranting menebal seperti
juga batang, sehingga pohon bertambah besar.
3.
Pertumbuhan
Primer
Terbentuknya bunga, dimulai dari alat kelamin betina atau
putik yang mengandung sel telur (ovarium) lalu dibuahi oleh alat kelamin jantan
atau benang sari yang mengandung sel sperma dan akhirnya membentuk lembaga atau
zigot. Sel induk lembaga atau zigot ini mengalami proses perkembangan yang
ditandai dengan adanya periode perlambatan pertumbuhan atau tidak ada sama
sekali pertumbuhan, sehingga bentuk zigot tidak mengalami perubahan atau tidak
mengalami pertambahan ukuran panjang.
Proses
perkembangan zigot dimulai dari sel induk yang membelah secara meiosis
menghasilkan empat sel haploid, artinya satu sel besar dan tiga sel kecil yang
melebur/melarut ke dalam sel besar. Selanjutnya sel haploid itu menyusun atau
mengumpulkan energi dari zat-zat makanan untuk mela- kukan pembelahan
berikutnya secara mitosis.
Pembelahan
mitosis sebenarnya adalah awal dimulainya proses pertum- buhan embrionik yang
ditandai dengan adanya periode percepatan pertum- buhan akibat terjadinya
pembelahan sel bertahap secara cepat dan terus menerus menghasilkan dua sel,
empat sel, delapan sel, enam belas sel, dan seterusnya, sehingga terjadi
penambahan/pemanjangan ukuran selnya. Se- lanjutnya membentuk kumpulan/kelompok
yang tumbuh menjadi embrio atau jaringan meristem atau jaringan embrional,
kemudian jaringan meristem ini tumbuh dan berkembang menjadi embrio yang
tersimpan dan terlindungi di dalam biji, kemudian tumbuh menjadi kecambah
hingga mencapai dewasa. Pertumbuhan pada embrio atau jaringan meristem dari
hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer ini disebut dengan
pertumbuhan primer.
Merupakan
pertumbuhan yang terjadi karena adanya meristem primer. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kegiatan
titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang dimulai
sejak tumbuhan masih berupa embrio.
Setelah
fase perkecambahan, diikuti pertumbuhan tiga sistem jaringan meristem primer
yang terletak di akar dan batang. Pada fase ini tumbuhan membentuk akar,
batang, dan daun. Tiga sistem jaringan primer yang terbentuk sebagai berikut.
a. Protoderm,
yaitu lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis.
b. Meristem
dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar yang mengisi lapisan korteks
pada akar di antara style dan epidermis.
c. Prokambium,
yaitu lapisan dalam yang akan berkembang menjadi silinder pusat, yaitu floem
dan xilem.
Pertumbuhan Primer pada Akar
Akar
muda yang keluar dari biji segera masuk ke dalam tanah, selanjutnya membentuk
sistem perakaran tanaman. Pada ujung akar yang masih muda, terdapat empat
daerah pertumbuhan sebagai berikut.
a. Tudung
akar (kaliptra)
Tudung
akar atau kaliptra berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan fisik ujung
akar terhadap tanah sekitar pertumbuhan. Fungsi lain ujung akar, yaitu
memudahkan akar menembus tanah karena tudung akar dilengkapi dengan sekresi
cairan polisakarida.
Perbedaan
antara tudung akar dikotil dan monokotil sebagai berikut.
·
Pada tudung akar dikotil, antara ujung
akar dengan kaliptra tidak terdapat batas yang jelas dan tidak memiliki titik
tumbuh pada kaliptra tersebut.
·
Pada tudung akar monokotil, antara ujung
akar dan kaliptra terdapat batas yang jelas atau nyata dan mempunyai titik
tumbuh tersendiri yang disebut kaliptrogen.
Sel-sel
kaliptra yang dekat dengan ujung akar mengan- dung butir-butir tepung yang
disebut kolumela.
b. Meristem
Meristem
merupakan bagian dari ujung akar yang selnya senantiasa mengadakan pembelahan
secara mitosis. Meristem ini terletak di belakang tudung akar. Pada tumbuhan
dikotil, sel-sel tudung akar yang rusak akan digantikan oleh sel-sel baru yang
dihasilkan oleh sel-sel me-ristem pri- mer dari perkembangan sel-sel meristem
apikal.
c. Daerah
pemanjangan sel
Daerah
pemanjangan sel terletak di belakang daerah meristem. Sel-sel hasil pembelahan
meristem tumbuh dan ber- kembang memanjang pada daerah ini. Aktivitas
pertumbuhan dan perkembangan memanjang dari sel mengakibatkan pem- belahan sel
di daerah ini menjadi lebih lambat dari bagian lain. Pemanjangan sel tersebut
berperan penting untuk mem- bantu daya tekan akar dan proses per- tumbuhan
memanjang akar.
d. Daerah
diferensiasi
Pada
daerah ini, sel-sel hasil pembelahan dan peman- jangan akan mengelompok se-suai
dengan kesamaan struktur. Sel-sel yang memiliki kesamaan struktur, kemu- dian
akan memperoleh tugas membentuk jaringan ter- tentu.
Pertumbuhan Primer pada Batang
Pertumbuhan
dan perkembangan primer pada batang meliputi daerah pertumbuhan (titik tumbuh),
daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Meristem apikal pada batang
dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas yang biasa
disebut kuncup. Di dalam kuncup, ruas batang dan tonjolan daun kecil
(primordia) memiliki jarak sangat pendek karena jarak internodus (antarruas)
sangat pendek. Pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel terjadi di dalam
internodus.
4.
Pertumbuhan
Sekunder
Merupakan
pertumbuhan yang terjadi karena adanya meristem sekunder. Pertumbuhan ini
disebabkan oleh kegiatan kambium yang bersifat meristematik kembali. Ciri-ciri
jaringan meristematik ini adalah mempunyai dinding yang tipis, bervakuola kecil
atau tidak bervakuola, sitoplasma pekat dan sel- selnya belum berspesialisasi.
Ketika pertumbuhan berlangsung secara aktif, sel-sel meristem membelah
membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru yang terbentuk itu pada awalnya rupanya
sama, tetapi setelah dewasa, sel-sel tadi berdiferensiasi menjadi jaringan
lain.
Pada
tumbuhan dikotil, selain terdapat jaringan meristem primer juga terdapat
jaringan meristem sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi pada jaringan meristem
sekunder berupa kambium gabus atau gabus. Fungsi kambium gabus adalah sebagai
perlindungan pada pertumbuhan sekunder yaitu per- tumbuhan organ tumbuhan
menjadi bertambah besar ukurannya. Contoh tumbuhan yang melakukan pertum- buhan
sekunder adalah pohon jati yang banyak terdapat di daerah Blora, Cepu, Jawa
Tengah.
Setelah
meristem primer membentuk jaringan permanen, kemudian meristem sekunder
mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada
tumbuhan dikotil, yaitu pembentukan kambium yang terbentuk dari parenkim atau
kolenkim.
Jika
sel kambium membelah ke arah luar, akan membentuk sel floem, sebaliknya jika
sel kambium membelah ke arah dalam akan membentuk xilem. Xilem dan floem yang
terbentuk dari aktivitas kambium disebut xilem sekunder dan floem sekunder. Pertumbuhan
xilem dan floem tersebut menyebabkan batang bertambah besar dan terbentuk lingkaran
tahun yang dipengaruhi oleh aktivitas pada musim kemarau dan musim penghujan.
Pada
awal pertumbuhan, kam- bium hanya terdapat pada jaringan ikat pembuluh (vasis)
yang disebut kambium intravaskuler atau kambium vasis, kambium ini dapat tumbuh
dengan arah yang berlawanan, yaitu yang tumbuh ke arah luar akan menjadi xilem
dan yang tumbuh kearah dalam akan membentuk floem. Selanjutnya pada pertumbuhan
sel jaringan parenkim yang berada di antara kambium intravaskuler akan tumbuh
dan berubah menjadi kam- bium baru yang disebut kambium intervaskuler.
Di
dalam perkembangannya, kambium intervaskuler akan tersambung dengan kambium
intravaskuler yang membentuk suatu lingkaran konsentris, bentuk lingkaran
konsentris pada tumbuhan dikotil sering disebut dengan lingkaran tahun. Contoh
batang tumbuhan dikotil yang mempunyai lingkaran tahun adalah pohon jati.
Lingkaran
tahun pada pohon jati terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan sekunder (kambium
gabus) yang berlangsung/berjalan tidak sepanjang tahun. Pertumbuhan sekunder
berlangsung hanya pada musim penghujan karena pada musim penghujan kebutuhan
air dan unsur hara cukup banyak tersedia untuk pertumbuhan tanaman tersebut,
dengan proses pertumbuhan seperti ini akan terbentuk suatu lingkaran yang
disebut lingkaran tahun.
Pada
umumnya tumbuhan dikotil seperti pohon jati memiliki kulit batang pecah-pecah
atau rusak. Kulit batang jati mengalami pecah- pecah, karena adanya aktivitas
kambium yang membentuk jaringan xilem dan floem lebih cepat dari pertumbuhan
kulit, sehingga akan mengakibatkan jaringan kulit paling luar seperti epidermis
dan korteks menjadi rusak atau pecah-pecah. Untuk mencegah terjadinya kerusakan
kulit terluarnya lebih lanjut, maka jaringan yang berada di sebelah dalam kulit
membentuk jaringan pelindung dari kerusakan berupa kambium gabus atau felogen.
Felogen membentuk jaringan yang tumbuh ke arah dalam disebut feloderm yang sel-
selnya hidup sedangkan jaringan yang tumbuh ke arah luar disebut felem yang
sel-selnya mati.
Jaringan
meristem ada dua jenis, yaitu:
a. Jaringan
meristem apex
Jaringan
ini terdapat pada ujung akar dan batang, yang berfungsi untuk mewujudkan
pertumbuhan primer.
b. Jaringan
meristem lateral
Jaringan
ini dapat membentuk pertumbuhan sekunder. Contoh yang sering kita temukan
adalah kambium, jaringan ini dapat menumbuhkan pertumbuhan lateral atau
menambah diameter dari bagian tumbuhan. Kambium didapatkan pada tumbuhan
dikotil dan Gymnospermae. Contoh yang lain adalah kambium gabus yang terdapat
pada batang dan akar tumbuhan berkayu atau pada bagian tumbuhan yang kena luka.
Aktivitas
kambium dipengaruhi oleh keadaan suatu iklim, sehingga sel-sel kayu yang
terbentuk pada musim penghujan berukuran besar, dan sel-sel yang terbentuk di
musim kemarau berukuran kecil-kecil. (Suroso AY, dkk. 2003: 71-72)
Pertumbuhan
ini terjadi pada tumbuhan Dicotyledoneae dan Gymnospermae. Pertumbuhan sekunder
disebabkan oleh kegiatan meristem sekunder, yang meliputi:
a. Kambium
gabus (felogen)
Pertumbuhan
felogen menghasilkan jaringan gabus.
Jaringan gabus berperan sebagai pelindung, yaitu menggantikan fungsi
epidermis yang mati dan terkelupas, juga merupakan bagian dari jaringan
sekunder yang disebut periderm.
b. Kambium
fasis
Berperan
membentuk xilem sekunder ke arah dalam dan membentuk floem sekunder ke arah
luar, selain itu juga menghasilkan sel-sel hidup yang berderet-deret menurut
arah jari-jari dari bagian xilem ke bagian floem yang disebut jari-jari
empulur. Bagian xilem lebih tebal dari pada bagian floem karena kegiatan
kambium ke arah dalam lebih besar daripada kegiatan ke arah luar.
c. Kambium
interfasis
Merupakan
kambium yang membentuk jari-jari empulur. Tumbuhan monokotil yang tidak
mempunyai kambium, tumbuh dengan cara penebalan. Tetapi pada umumnya,
pertumbuhan terjadi karena adanya peningkatan banyaknya dan ukuran sel.
Pertumbuhan pada tumbuhan dikotil yang berkayu menyangkut kedua aktivitas
tersebut, sel- sel baru yang kecil yang dihasilkan kambium dan meristem apikal,
kemudian sel-sel ini membesar dan berdifferensiasi. (Kimball, 1992: 411)
5.
Pertumbuhan
Terminal
Terjadi
pada ujung akar dan ujung batang tumbuhan berbiji yang aktif tumbuh. Terdapat 3
daerah (zona) pertumbuhan dan perkembangan.
a. Daerah
pembelahan (daerah meristematik)
Merupakan
daerah yang paling ujung dan merupakan tempat terbentuknya sel-sel baru. Sel-sel di daerah ini mempunyai inti sel yang
relatif besar, berdinding tipis, dan aktif membelah diri.
b. Daerah
pemanjangan
Merupakan
daerah hasil pembelahan sel-sel meristem.
Sel-sel hasil pembelahan tersebut akan bertambah besar ukurannya
sehingga menjadi bagian dari daerah perpanjangan. Ukuran selnya bertambah
beberapa puluh kali dibandingkan sel-sel meristematik.
c. Daerah
diferensiasi
Merupakan
daerah yang terletak di bawah daerah pemanjangan. Sel- sel di daerah ini
umumnya mempunyai dinding yang menebal dan beberapa di antaranya mengalami
diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan empulur. Sel yang lain
berdiferensiasi menjadi jaringan parenkim, jaringan penunjang, dan jaringan
pengangkut (xilem dan floem).
Beberapa teori tentang
titik tumbuh adalah sebagai berikut.
1) Teori
Histogen dari Hanstein
Teori
Histogen menyatakan bahwa titik tumbuh batang seakan-akan dapat dibedakan
menjadi tiga lapisan yang membentuk jaringan/histogen.
2) Teori
Tunika dan Korpus dari Schmidt
Teori
Tunika menyatakan bahwa titik tumbuh hanya dapat dibeda- kan menjadi dua bagian
saja.
·
Tunika, yaitu lapisan pinggir, terdiri
atas sel-sel yang membelah mengakibatkan bertambah luasnya permukaan titik
tumbuh.
·
Korpus, adalah bagian yang terdapat di
sebelah dalam tunika, terdiri atas sel-sel yang membelah ke segala arah.
Alat Pengukur Kecepatan
Pertumbuhan Tumbuhan
1) Mistar
Dengan
menggunakan alat ini kita dapat mengetahui kecepatan pertumbuhan. Cara mengukur
mula- mula kecambah diberi tanda dengan menggunakan tinta tahan air dengan jarak
tertentu. Alat ini juga untuk mengetahui bagian yang mengalami pertambahan
panjang paling cepat.
2) Auksanometer
(Busur Tumbuh)
Cara
penggunaan auksanometer adalah sebagai berikut.
·
Ikatkan
tali atau benang pada ujung batang tanaman dalam pot yang sudah disiapkan.
Benang tersebut diletakkan pada katrol
yang ditempatkan tepat di atas tanaman.
·
Kemudian pada katrol diletakkan alat
penunjuk yang dapat berputar mengikuti perputaran katrol.
·
Pada ujung benang yang lain diikatkan
sebuah beban pemberat.
·
Aturlah penunjuk pada benang katrol tadi
agar bergerak sepanjang busur yang telah diberi skala.
·
Amatilah selama beberapa hari busur
penunjuknya dan hitunglah berapa pertambahan tinggi atau panjang batang itu.
C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan
Suatu
tanaman dalam proses pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor luar
(eksternal). Faktor-faktor eksternal atau lingkungan yang berpengaruh sebagai
berikut.
a. Iklim
seperti cahaya, temperatur udara, air, angin, matahari dan gas.
b. Tanah
meliputi tekstur dan struktur tanah, bahan organik, ketersediaan nutrien, dan
pH.
c. Biologis,
seperti gulma, serangga, mikroorganisme penyebab penyakit, nematoda macam-macam
tipe herbivora, mikroorganisme tanah seperti bakteri pemfiksasi N2 dan bakteri
denitrifikasi serta mikorhiza.
1.
Faktor
Dalam (Internal) yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan
Faktor
dalam yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah gen
dan zat pengatur tumbuh.
a. Faktor
Genetik
Faktor
penurunan sifat pada keturunan terkandung di dalam gen. Informasi genetik pada
gen mengendalikan terben- tuknya sifat penampakan secara fisik (fenotip)
melalui interaksinya dengan faktor lingkungan. Sifat menurun tersebut disebut
hereditas. Sifat menurun merupakan gen yang terdapat pada setiap kromosom di
dalam inti sel jaringan penyusun organ tubuh tumbuhan.
b. Zat
Pengatur Tumbuh (Hormon)
Istilah
hormon pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli botani dari Belanda bernama
Friedrich Agust Ferdinand Went (1863– 1935). Went berpendapat bahwa hormon
tumbuh merupakan zat yang penting dalam pertumbuhan tanaman. Hormon tumbuh
tersebut juga disebut zat tumbuh yang komponennya terdiri atas senyawa protein
dengan substansi kimia yang aktif.
Zat
pengatur tumbuh (hormon) pada tanaman ialah senyawa organik yang dalam jumlah
sedikit dapat mendukung, meng- hambat, dan mengubah proses fisiologis tumbuhan.
Pada konsentrasi tertentu hormon dapat memacu pertumbuhan, tetapi pada
konsentrasi yang tinggi dapat menekan pertum- buhan. Macam-macam hormon sebagai
berikut.
1) Auksin
atau AIA (Asam Indol Asetat)
Hormon
auksin pertama kali ditemukan oleh Went yang terdapat pada ujung koleoptil
kecambah gandum (Avena sativa). Pada penelitian Went lebih lanjut, ternyata
diketahui hormon auksin juga ditemukan pada ujung koleoptil kecambah tanaman
yang lain. Hormon auksin merupakan senyawa kimia Indol Asetic Acid (IAA)
dihasilkan dari sekresi pada titik tumbuh yang terletak pada ujung tunas
(terdiri atas batang dan daun), ujung akar, daun muda, bunga, buah, dan
kambium. Jika hormon auksin berada di ujung tunas, maka akan diangkut oleh
jaringan berkas pembuluh (xilem dan floem) menuju ke tunas untuk tumbuh dan
pemanjangan sel-sel jaringan batangnya.
Pengaruh
hormon auksin dalam konsentrasi yang berbeda pada bagian tubuh tanaman
mengakibatkan terjadinya pertumbuhan yang tidak seim- bang. Bagian yang
mengandung auksin lebih banyak memiliki kecepatan tumbuh yang lebih besar.
Adapun bagian yang kekurangan akan mengalami pertumbuhan lebih lambat. Jika ini
terjadi pada pucuk batang, terjadi pembengkokan arah pertum- buhan. Pengaruh
auksin terhadap perkembangan sel memperlihatkan bahwa auksin dapat menaikkan
tekanan osmotik, meningkatkan permeabilitas sel terhadap air, menyebabkan
pengurang- an tekanan pada dinding-dinding sel, meningkatkan sin- tesis
protein, meningkatkan plas-tisitas, mengembangnya dinding sel.
Hormon
auksin selain berfungsi merangsang perpanjangan sel-sel batang dan menghambat
perpanjangan sel-sel akar, juga berfungsi merangsang pertumbuhan akar sam- ping
(lateral) dan akar serabut yang berfungsi sebagai penyerapan air dan mineral,
mempercepat aktivitas pembelahan sel-sel titik tumbuh kambium akar dan batang,
menyebabkan terjadinya diferensiasi sel menjadi jaringan berkas angkut xilem,
dan merangsang terjadinya pembentukan bunga dan buah.
Fungsi
auksin, yaitu:
·
Merangsang perpanjangan sel.
·
Merangsang pembentukan bunga dan buah.
·
Merangsang pemanjangan titik tumbuh.
·
Mempengaruhi pembengkokan batang.
·
Merangsang pembentukan akar lateral.
·
Merangsang terjadinya proses
diferensiasi.
2) Gibberellin
Giberelin
pertama kali ditemukan pada tumbuhan sejenis jamur Giberella fujikuroi
(Fusarium moniliformae) oleh F.Kurusawa, seorang berkebangsaan Jepang. Hormon
ini berpengaruh terhadap sifat genetik, pembungaan, penyinaran, dan mobilisasi
karbohidrat selama perkecambahan. Hormon ini berperan dalam mendukung
perpanjangan sel, aktivitas kambium mendukung pembentukan RNA baru, dan
sintesis protein.
Giberelin
adalah zat tumbuh yang sifatnya sama atau menyerupai hormon auksin, tetapi
fungsi giberelin sedikit ber- beda dengan auksin. Fungsi giberelin adalah
membantu pembentukan tunas/ embrio, menghambat perkecambahan dan pembentukan
biji. Hal ini terjadi apabila giberelin diberikan pada bunga maka buah yang terbentuk
menjadi buah tanpa biji dan sangat nyata mempengaruhi pemanjangan dan
pembelahan sel. Hal itu dapat dibuk- tikan pada tumbuhan kerdil, jika diberi
giberelin akan tumbuh normal, jika pada tumbuhan normal diberi giberelin akan
tumbuh lebih cepat.
Fungsi
gibberellin, yaitu:
·
Merangsang pembelahan sel kambium.
·
Merangsang pembungaan lebih awal sebelum
waktunya.
·
Merangsang pembentukan buah tanpa biji.
·
Merangsang tanaman tumbuh sangat cepat
sehingga mempunyai ukuran raksasa. (Dwidjoseputro, 1992: 197)
3) Sitokinin
Ada
dua jenis hormon sitokinin, yaitu zeatin (merupakan sitokinin alami yang
terdapat pada biji jagung) dan kinetin yang merupakan sitokinin buatan. Fungsi
sitokinin adalah untuk merangsang pembelahan sel, memperkecil dominasi apikal,
mengatur pembentukan bunga dan buah, membantu pembentukan akar, tunas, menunda
pengguguran daun, dan menghambat proses penuaan. Efek dari sitokinin berlawanan
dengan auksin pada tumbuhan.
Contoh
jika sitokinin banyak diberikan pada tumbuhan maka akan banyak tumbuh tunas, tetapi
jika sedikit diberikan pada tumbuhan maka akan terbentuk banyak akar. Hal ini
terjadi karena sitokinin dapat menghentikan dominasi pertumbuhan kuncup atas
(apikal) dan merangsang pertumbuhan kuncup samping (lateral).
Fungsi
sitokinin yaitu:
·
Merangsang proses pembelahan sel.
·
Menunda pengguguran daun, bunga, dan
buah.
·
Mempengaruhi pertumbuhan tunas dan akar.
·
Meningkatkan daya resistensi terhadap
pengaruh yang merugikan. seperti suhu rendah, infeksi virus, pembunuh gulma,
dan radiasi.
·
Menghambat (menahan) menguningnya daun
dengan jalan membuat kandungan protein dan klorofil yang seimbang dalam daun
(senescens).
4) Asam
Absitat (ABA)
Asam
absisat merupakan hormon yang dapat menghambat pertumbuh- an tanaman
(inhibitor) yaitu bekerja berlawanan dengan hormon auksin dan giberelin dengan
jalan mengurangi atau memperlambat kecepatan pem- belahan dan pembesaran sel.
Asam absisat akan aktif pada saat tumbuhan berada pada kondisi yang kurang
baik, seperti pada musim dingin, musim kering, dan musim gugur.
Pada
saat tumbuhan mengalami kondisi yang kurang baik, misalnya ketika kekurangan
air di musim kering, maka tumbuhan tersebut mengalami dormansi yaitu
daun-daunnya akan digugurkan dan yang tertinggal adalah tunas-tunasnya. Dalam
keadaan demikian asam absisat terkumpul/terakumulasi pada tunas yang terletak
pada sel penutup stomata, hal ini menyebabkan stomata menutup, sehingga
penguapan air berkurang dan keseimbangan air di dalam tubuh tumbuhan
terpelihara sehingga pertumbuhan tunasnya terhambat yang disebabkan melambatnya
kecepatan pembelahan dan pembesaran sel-sel tunasnya.
Fungsi
asam absisat, yaitu:
·
Menghambat perkecambahan biji.
·
Mempengaruhi pembungaan tanaman.
·
Memperpanjang masa dormansi umbi-umbian.
·
Mempengaruhi pucuk tumbuhan untuk
melakukan dormansi.
·
Mengurangi kecepatan pertumbuhan dan
pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh
5) Gas
Etilen
Gas
etilen adalah suatu gas yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua sehingga buah
menjadi matang. Jika buah tua yang masih berwarna hijau disimpan dalam tempat
tertutup dan dibiarkan beberapa hari, akhirnya menjadi matang dan berwarna
kuning sampai merah. Dalam hal ini terjadi perubahan warna dari hijau menjadi
kuning sampai merah pada buah karena keluarnya gas etilen dari buah tersebut. Hormon
ini berperan pada proses pema- tangan buah. Hubungan etilen dengan auksin yaitu
etilen memengaruhi pembentukan protein yang diperlukan dalam aktivitas
pertumbuhan.
Salah
satu cara mencegah terjadinya pembusukan atau kerusakan pada saat pemeraman
buah adalah pada saat buah tua dipetik/dipanen masih berwarna hijau, kemudian
dikemas atau disimpan pada tempat yang berventilasi untuk mencegah buah tidak
cepat masak/matang, sehingga sesampainya di tempat tujuan buah tersebut baru
matang dan tidak rusak atau busuk.
Fungsi
gas etilen, yaitu:
·
Membantu memecahkan dormansi pada
tanaman, misalnya pada ubi dan kentang.
·
Mendukung pematangan buah.
·
Mendukung terjadinya abscission (pelapukan)
pada daun.
·
Mendukung proses pembungaan, yang
bekerja bersamaan dengan auksin dan bersama giberelin dapat mengatur perbandingan bunga betina dan jantan pada
tumbuhan berumah satu.
·
Menghambat pemanjangan akar pada
beberapa spesies tanaman dan dapat menstimulasi pemanjangan batang.
·
Menstimulasi perkecambahan.
·
Mendukung terbentuknya bulu-bulu akar.
·
Menyebabkan pertumbuhan batang menjadi
kokoh dan tebal
6) Asam
Traumalin
Asam
traumalin disebut sebagai hormon luka/kambium karena hormon ini berperan
apabila tumbuhan mengalami kerusakan jaringan. Jika terluka, tumbuhan akan
merangsang sel-sel di daerah luka menjadi bersifat meristem lagi sehingga mampu
mengadakan pembelahan sel untuk menutup luka tersebut.
Vitamin
dapat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan, misalnya vitamin B12,
vitamin B1, Vitamin B6, vitamin C (asam askorbat). Vitamin-vitamin tersebut
berfungsi dalam proses pembentukan hormon dan berfungsi sebagai koenzim.
7) Kalin
Kalin
merupakan hormon yang mempengaruhi pembentukan organ. Berdasarkan organ yang
dipengaruhinya, kalin dibedakan atas:
·
Rhizokalin, mempengaruhi pembentukan
akar.
·
Kaulokalin, mempengaruhi pembentukan
batang.
·
Filokalin, mempengaruhi pembentukan
daun.
·
Antokalin, mempengaruhi pembentukan
bunga.
2.
Faktor
Luar (Eksternal) yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan
1) Nutrisi
Nutrisi
terdiri atas unsur-unsur atau senyawa-senyawa kimia sebagai sumber energi dan
sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama
pertumbuhan.
Nutrisi
umumnya diambil dari dalam tanah dalam bentuk ion dan kation, sebagian lagi
diambil dari udara.
Unsur-unsur
yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak disebut unsur makro (C, H, O, N, P, K,
S, Ca, Fe, Mg). Adapun unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut
unsur mikro (B, Mn, Mo, Zn, Cu, Cl). Jika salah satu kebutuhan unsur-unsur
tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kekurangan unsur yang disebut
defisiensi. Defisiensi meng- akibatkan pertumbuhan menjadi terhambat.
Jika
di dalam tanah terdapat sedikit unsur hara seperti kekurangan nitrogen, maka
pertumbuhan akar akan lebih cepat atau lebih besar, sedang- kan pertumbuhan
tajuknya menjadi terhambat atau kecil. Sebaliknya jika di dalam tanah kaya
nitrogen maka pertumbuhan tajuk akan lebih cepat daripada pertumbuhan akarnya.
Dengan demikian terdapat hubungan erat antara pertumbuhan akar dan tajuk
tanaman. Akar berfungsi untuk menye- rap air tanah dan tajuk berfungsi untuk
melakukan sintesis senyawa organik (makanan).
2) Air
Air
berperan di dalam melarutkan unsur hara dalam proses penyerapan. Air dibutuhkan
tumbuhan sebagai pelarut bagi kebanyakan reaksi dalam tubuh tumbuhan dan
sebagai medium reaksi enzimatis. Sebagai pelarut, air juga me- mengaruhi kadar
enzim dan substrat sehingga secara tidak langsung memengaruhi laju metabolisme.
Kekurangan air pada tanah menyebabkan terhambatnya proses osmosis. Proses
osmosis akan terhenti atau berbalik arah yang berakibat keluarnya materi-materi
dari protoplasma sel-sel tumbuhan, sehingga tanaman kering dan mati.
Fungsi
air bagi tumbuhan adalah sebagai berikut.
·
Fotosintesis
·
Mengedarkan hasil-hasil fotosintesis ke
seluruh bagian tumbuhan.
·
Sebagai pelarut inti sel dalam proses
pertumbuhan dan perkembangan.
·
Menentukan proses transportasi unsur
hara yang ada di dalam tanah.
·
Berperan dalam proses metabolisme sel.
·
Mengaktifkan reaksi-reaksi enzim.
·
Membantu proses perkecambahan biji
·
Menjaga (mempertahankan kelembapan).
·
Meningkatkan tekanan turgor sehingga
merangsang pembelahan sel.
·
Menghilangkan asam absisi.
3) Cahaya
Matahari
Cahaya
mutlak diperlukan dalam proses fotosintesis. Cahaya secara langsung berpengaruh
terhadap pertumbuhan setiap tanaman.
Pengaruh cahaya secara langsung dapat diamati dengan membandingkan
tanaman yang tumbuh dalam keadaan gelap dan terang.
Pada
keadaan gelap, pertumbuhan tanaman mengalami etiolasi yang ditandai dengan
pertumbuhan yang abnormal (lebih panjang), pucat, daun tidak berkembang, dan
batang tidak kukuh. Sebaliknya, dalam keadaan terang tumbuhan lebih pendek,
batang kukuh, daun berkembang sempurna dan berwarna hijau. Biji tumbuhan yang
berkecambah dan tumbuh di tempat yang gelap/tidak ada cahaya ternyata tumbuhnya
tidak normal dengan ciri tumbuhnya sangat cepat, perawakan tumbuhan tampak
tinggi dan ramping, batangya lemah dan batang tidak berwarna hijau tetapi
pucat. Gejala ini disebut etiolasi.
Dalam
fotosintesis, cahaya berpengaruh langsung terhadap ketersediaan makanan.
Tumbuhan yang tidak terkena cahaya tidak dapat membentuk klorofil, sehingga
daun menjadi pucat.
Setiap
tumbuhan mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap periode penyinaran cahaya
matahari, yang disebut fotoperiodisme. Di daerah yang beriklim sedang akan
mengalami empat musim sehingga tumbuh-tumbuhan akan mengalami penyinaran yang
bervariasi setiap musim.
Berdasarkan
respon tumbuhan terhadap periode penyinaran inilah, tumbuhan dapat
dikelompokkan menjadi: tumbuhan berhari pendek, tumbuhan berhari netral, dan
tumbuhan berhari panjang.
·
Tumbuhan berhari pendek (short day
plant)
Tumbuhan
berhari pendek merupakan tumbuhan yang dapat berbunga ketika periode gelap
lebih panjang dari pada pencahayaan Berbunga jika panjang hari kurang dari
periode kritis tertentu, misalnya kastuba (Euphorbia pulcherima), ubi jalar
(Ipomoea batatas), nanas (Ananas commosus), dan padi (Oryza sativa), bunga
dahlia, aster, strawberi, krisan.
Panjang hari harus kurang dari 11 hingga 15 jam agar pembungaan terjadi.
·
Tumbuhan berhari netral (day-neutral
plant)
Tumbuhan
berhari netral merupakan tumbuhan berbunga yang tidak dipengaruhi oleh
lamanya/panjangnya hari penyinaran. Misalnya bunga matahari, mawar, jagung
(Zea mays), dan kipas.
·
Tumbuhan berhari panjang (long day
plant)
Tumbuhan
berhari panjang merupakan tumbuhan yang berbunga ketika periode pencahayaan
lebih lama/panjang daripada periode gelap. Misalnya bayam, selada, kentang, gandum,
tanaman jarak (Rhicinus communis) dan kentang (Solanum tuberosum). Panjang hari
harus lebih dari 12 hingga 14 jam agar pembungaan terjadi.
4) Suhu/Temperatur
Suhu
optimum (10°C hingga 38°C) merupakan suhu yang paling baik untuk pertumbuhan.
Suhu minimum (± 10°C) merupakan suhu terendah di mana tumbuhan masih dapat
tumbuh. Suhu maksimum (30°C hingga 38°C) merupakan suhu tertinggi dimana
tumbuhan masih dapat tumbuh.
Setiap
proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan selalu dipengaruhi oleh suhu
lingkungannya. Agar pertumbuhan dan perkem- bangan pada tumbuhan optimal, maka
diperlukan adanya suhu ideal yang disebut temperatur optimum. Di Indonesia pada
daerah tropis temperatur optimum tumbuhan berkisar antara 22o - 37o C, di
daerah dingin atau kutub temperatur optimumnya akan lebih rendah daripada
daerah tropis dan sebaliknya di daerah panas seperti hutan pasir akan lebih
tinggi dari daerah tropis.
Contohnya
pertumbuhan jagung berkisar antara 30oC–35oC. Jika tumbuhan masih mampu
melakukan pertumbuhan dan perkembangan pada temperatur rendah disebut
temperatur minimum, sebaliknya jika tumbuhan masih mampu tumbuh dan berkembang
pada temperatur tertinggi disebut temperatur maksimum. Apabila tumbuhan berada
lebih rendah dari tempera- tur minimum atau lebih tinggi dari temperatur
maksimum, maka tumbuhan tersebut akan mati.
5) Kelembapan
Udara
Kelembapan
ada kaitannya dengan laju transpirasi melalui daun karena transpirasi akan
terkait dengan laju pengangkutan air dan unsur hara terlarut. Bila kondisi
lembap dapat dipertahankan maka banyak air yang diserap tumbuhan dan lebih
sedikit yang diuapkan. Kondisi ini mendukung aktivitas pemanjangan sel sehingga
sel-sel lebih cepat mencapai ukuran maksimum dan tumbuh bertambah besar.
Umumnya
tanah dan udara sekitar yang kurang lembab (airnya cukup) akan sangat baik atau
cocok bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, karena pada kondisi seperti
itu tanaman menyerap banyak air dan penguapan (transpirasi) air semakin
menurun, sehingga memungkinkan cepat terjadinya pembelahan dan pemanjangan
sel-sel untuk mencapai ukuran maksimum. Tetapi ada jenis tumbuhan pada proses pertumbuhan
dan perkembangannya secara optimal justru berada pada kondisi tidak lembab atau
kering, contohnya pohon mangga yang akan bertunas dan bersemi, bahkan berbuah
pada saat musim kemarau yang kurang air.
6) Oksigen
Untuk pemecahan senyawa bermolekul besar (saat
respirasi) agar menghasilkan energi yang diperlukan pada proses pertumbuhan dan
perkembangannya.
7) Derajat
Keasaman/pH
Derajat
keasaman atau pH tanah sangat berpengaruh terhadap pertum- buhan dan
perkembangan suatu tanaman. Contohnya tanah yang bersifat asam terhadap tanah
padsolik merah kuning (PMK), agar tanaman dapat tumbuh dengan baik maka jenis
tanah ini ditambahkan keasaman dengan pengapuran.
Sumber:
Subardi, Nuryadi, dan Shidiq Pramono. 2008. Biologi 3 : Untuk Kelas XII SMA dan MA.
Jakarta: CV. Usaha Makmur




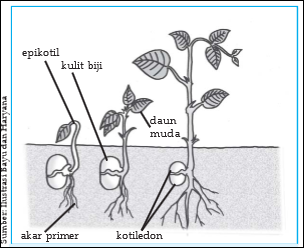

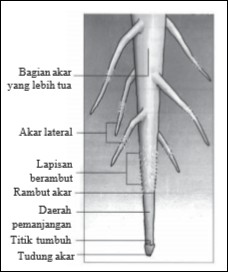








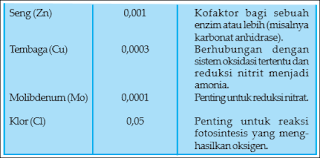
permisi min numpang share ya :)
ReplyDeletebosan tidak tahu mesti mengerjakan apa ^^
daripada begong saja, ayo segera bergabung dengan kami di
F*A*N*S*P*O*K*E*R cara bermainnya gampang kok hanya dengan minimal deposit 10.000
ayo tunggu apa lagi buruan daftar di agen kami ^^